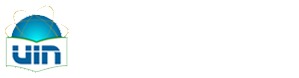Mahmud Yunus, Gelar Pahlawan Nasional dan Museum Pendidikan Islam (Seri I)

Dr. Abdul Rozak, M.Si. (Dosen FITK UIN Jakarta dan Pemerhati Pendidikan)
Pendahuluan Ranah Minang merupakan daerah yang secara ekologis menjadi daerah yang snagat subur bukan hanya dari sisi tumbuh suburnya pepohonan, sayur mayor dan buah-buahan serta hijaunya pohon padi seperti daerah lain di Indonesia, tapi dari ranah Minang juga subur dan banyak lahir pejuang, ulama dan tokoh bangsa dalam berbagai bidang keahlian dan keilmuan jauh sebelum perjuangan kemerdekaan, semasa perjuangan kemerdekaan dan hingga saat ini yang jumlahnya sangat banyak dan telah mendunia serta dalam kontek nasional juga sudah ada yang mendapat gelar pahlawan nasional.. Sejak jaman sebelum pergerakan kemerdekaan ada Syeckh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi (Seorang ulama asal Minang yang menjadi guru para ulama Indonesia dan menjadi Imam Masjidil Haram Makkah). Pada jaman perjuangan kemerdekaan ada Moh. Hatta, Moh. Yamin, Agus Salim, Tan Malaka, Soetan Sjahrir, Moh. Natsir, Buya Hamka, Mahmud Yunus, dan hingga kini ranang minang terus subur melahirkan tokoh, ulama, cendekiawan, intelektual dan sastrawan antara lain Prof. Deliar Noer, Prof. Taufik Abdullah, Prof. Azyumardi Azra, Prof. Buya A. Syafii Ma’arif. Dari kalangan astrawan anatara lain AA Navis, Usmar Ismail, Taufik Ismail, Diantara tokoh, ulama dan pemikir dari ranah Minang yang aktivitasnya sejak awal terfokus dalam dunia pendidikan yaitu Moh. Syafei, Rasuna Said, Rohana Kudus, Rahmah El Yunusiyyah, Prof. Mahmud Yunus dan tokoh lainnya. Mahmud Yunus kecil lahir di Sungayang, Tanah Datar, Minangkabau, 10 Februari 1899 dari pasangan Yunus dan Hafsyah yang berasal dari keluarga petani. Mahmud Yunus merupakan anak sulung dari tujuh bersaudara tumbuh dan besar di tengah keluarga ibunya. Sejak kecil Mahmud Yunus telah memperlihatkan minat terhadap ilmu agama seperti belajar Al-Qur'an di Surau Talang kepada kakeknya dan khatam 30 juz dalam usia tujuh tahun. Setelah itu, ia menggantikan kakenya mengajar di surau. Pada tahun 1908, ia masuk ke sebuah Sekolah Desa di Sungayang. Karena jemu dengan pelajaran yang sering diulang di kelas, setelah tahun keempat ia pindah ke Madras School pimpinan Muhammad Thaib Umar di Surau Tanjung Pauh. Ia belajar setiap hari dari pagi sampai siang. Namun, ia menarik diri dari mengajar di surau ketika berumur 12 tahun, dan pada umur 14 tahun ia dipercaya menjadi mudir (guru bantu) di Madras School tersebut. Pada tahun 1917, ketika Muhammad Thaib Umar jatuh sakit, Yunus ditunjuk untuk memimpin Madras School. Ketika berlangsung rapat besar ulama Minangkabau tahun 1919 di Surau Jembatan Besi, Padang Panjang, Mahmud Yunus hadir mewakili Muhammad Thaib Umar. Rapat ini meresmikan berdirinya Persatuan Guru Agama Islam (PGAI), sebagai organisasi perkumpulan ulama yang bergerak di bidang pendidikan. Mahmud Yunus menjadi salah seorang anggota terawal PGAI sejak didirikan. Pada akhir tahun 1919, Mahmud Yunus bersama-sama guru Madras School mendirikan cabang perkumpulan pelajar Islam Sumatera Thawalib di Sungayang. Ia menggerakkan kegiatan di bidang pendidikan melalui majalah Islam Al-Basyir. Majalah ini terbit perdana pada Februari 1920 dengan Mahmud Yunus sendiri sebagai pemimpin redaksinya. Dalam perjalanan intelektualnya Mahmud Yunus bersentuhan intelektual secara tidak langsung dengan ulama dan pemikir Islam modernis yaitu Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dari Mesir lewat bacaanya pada Majalah Al-Manar yang merupakan majalah yang di dalamnya memuat tulisan kedua ulama dan tokoh modernis Islam tersebut yang dikenal pembawa aliran rasional dalam Islam. Melalu pembacaanya dari majalah al-Manar, Mahmud Yunus berkeinginan untuk belajar ke Mesir dalam rangka menambah keluasan dan kedalaman ilmu keislaman yang sudah diperoleh sebelumnya. Dalam perjalanan belajar ke Mesir Mahmud Yunus sempat mengalami hambatan karena tidak memperoleh visa dari Pemerintahan Kolonial Inggris pada tahun 1920, namun ia tidak putus asa dan kehilangan asa dimana pada akhirnya Mahmud Yunus dapat berangkat ke Mesir lewat Penang, Malaysia pada Maret 1923. Dalam usahanya untuk perjalanan belajar ke Mesir, Mahmud Yunus dibantu mamaknya, Datuk Sinaro Sati mengurus visa di Padang dan juga dibantu biaya yang diperlukan selama perjalanan menuju Mesir. Langkah Pembaharuan Pendidikan : Memimpin Sekolah-sekolah Islam Sebelum berangkat ke Mesir, Mahmud Yunus terlebih dahulu menunaikan ibadah haji di Mekkah. Usai menunaikan ibadah haji, ia menuju Kairo dan mendaftar sebagai mahasiswa di Universitas Al-Azhar sebagai universitas terkemuka terutama dalam studi keislaman. Selama di tahun awal di Mesir ia menghabiskan satu tahun untuk memperoleh ijazah Syahadah Alimiyah (setara dengan magister) dan tercatat sebagai orang Indonesia kedua yang lulus di Universitas Al-Azhar setelah Janan Thaib. Dalam pendalaman dan pengembangan keilmuan, Mahmud Yunus mengikuti saran gurunya di Universitas Al-Azhar, dimana ia melanjutkan kuliah ke Universitas Darul Ulum (kini berada dalam Universitas Kairo Mesir). Ia diterima sebagai mahasiswa di kelas bagian malam dimana keseluruhan mahasiswanya berkebangsaan Mesir kecuali ia sendiri. Selama di Universitas Darul Ulum, ia mendapatkan pengecualian membayar uang kuliah atas kebijakan Menteri Pendidikan Mesir. Ia lulus di bidang ilmu kependidikan pada Mei 1930 setelah empat tahun di Universitas Darul Ulum dengan memperoleh ijazah diploma guru. Mahmud Yunus adalah mahasiswa asing pertama yang tamat dari Universitas Darul Ulum. Pada bulan Oktober 1930, Mahmud Yunus bersiap kembali ke Indonesia.Setibanya di kampung halamannya pada awal tahun 1931, Mahmud Yunus mulai memusatkan perhatian pada peningkatan mutu sekolah-sekolah agama sebagai kelanjutan minat dan fokusnya dalam pembenahan dan pembaharuan bidang pendidikan. Tahun pertama di lembaga tersebut, ia memperbarui Madras School di Sungayang dengan menerapkan sistem klasikal sebagaimana lazimnya sekolah-sekolah pemerintah. Lewat Madras School, ia mengenalkan pembagian jenjang madrasah yang dikenal di Indonesia saat ini yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Namun, lembaga pendidikan ini terpaksa ditutup pada tahun 1933, setahun setelah pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan kebijakan pembatasan berdirinya sekolah Islam atau dikenal dengan Kebijakan Ordonansi Sekolah Liar. Pada tahun berikutnya, Mahmud Yunus meninggalkan desa Sungayang untuk melaksanakan aktivitas mengajar dan memimpin sekolah umum KMI (Kulliyyatul Muallimin Al-Islamiyyaah) yaitu Normal Islamic School (NIS) di Padang sebuah lembaga pendidikan yang didirikan PGAI pada 1 April 1931. Sekolah ini merupakan sekolah lanjutan tingkat atas untuk mendidik calon guru, dimana murid di sekolah ini adalah lulusan madrasah minimal tujuh tahun. Di satuan pendidikan ini Mahmud Yunus mengajar bahasa Arab, memasukkan mata pelajaran agama Islam ke dalam kurikulum, dan menambahkan beberapa cabang pengetahuan umum seperti ilmu alam, tata buku, dan kesehatan dalam kurikulum sekolah tersebut. Sebagian buku ajar yang dipakai untuk keperluan pengajaran adalah tulisannya sendiri yang ia susun sewaktu belajar di Mesir. Ia memimpin NIS sampai tahun 1938 dan kelak kembali memimpin pada tahun 1942 sampai 1946. Dalam perjalanan berikutnya Mahmud Yunus pada 1 November 1940 dipercaya memimpin Sekolah Tinggi Islam (STI) di Padang sebuah lembaga pendidikan tinggi yang didirikan oleh PGAI. STI tercatat sebagai perguruan tinggi Islam paling awal di Indonesia. Pada 9 Desember 1940, STI membuka dua fakultas yaitu Fakultas Syariat dan Fakultas Pendidikan & Bahasa Arab. Namun, STI hanya berjalan sekitar dua tahun karena setelah Padang diduduki tentara Jepang pada 1 Maret 1942, perguruan tinggi termasuk STI ini dilarang beroperasi dan ditutup oleh pemerintah pendudukan. Langkah Pembaharuan Pendidikan : Memperkenalkan Mata Pelajaran Agama di Sekolah Gerakan pembaharua pendidikan terus dilakukan Mahmud Yunus diantaranya memasukkan mata pelajaran agama Islam ke dalam kurikulum sekolah-sekolah pemerintah yang waktu itu tidak ada dan belum jadi bagian kurikulum sekolah pada era setelah kemerdekaan. Usul ini diterima oleh Jawatan Pengajaran Sumatera Barat, yang waktu itu dikepalai oleh Saaduddin Jambek yang merupakan ulama yang peduli terhadap pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah. Mulai 1 April 1946 diterapkan mata pelajaran agama Islam di sekolah seluruh Sumatera Barat. Untuk keterlaksanaan dalam pembelajaran, oleh Jawatan Pengajaran Sumatera Barat (sekarang Dinas Pendidikan provinsi), Mahmud Yunus dipercaya untuk menyusun kurikulum mata pelajaran agama Islam dan menentukan buku-buku ajar sebagai buku pegangan untuk keperluan pengajaran. Dalam perjalanan tugasnya Mahmud Yunus pada November 1946 dipindahtugaskan ke Pematangsiantar dan diangkat sebagai Kepala Bagian Agama Islam Jawatan Agama Provinsi Sumatera untuk Memastikan pelaksanaan pembelajaran agama Islam di sekolah. Pada Januari 1947, Mahmud Yunus kembali mengusulkan mata pelajaran Agama Islam masuk dalam kurikulum sekolah kepada Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Provinsi Sumatera. Usul ini mendapat rspon dan persetujuan, sehingga pada Maret 1947, mata pelajaran Agama Islam masuk secara resmi ke dalam kurikulum sekolah pemerintah di seluruh Sumatera. Seiring dengan itu, pemerintah provinsi mengadakan kursus untuk penyediaan guru-guru agama di Pematangsiantar selama sebulan penuh. Kursus ini dikuti oleh utusan dari seluruh daerah di Sumatera dan sebagai pimpinan kursus dipercayakan oleh Mahmud Yunus. Pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), Mahmud Yunus membuka sekolah-sekolah darurat. Ia sempat mengemukakan rencana mendirikan Madrasah Tsanawiyah untuk seluruh Sumatera. Rencana ini mendapat persetujuan dari Menteri Agama PDRI. Setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada pemerintah RI, Madrasah Tsanawiyyah yang pada waktu itu bernama Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) dibuka di Sumatera Barat. Madrasah ini diselenggarakan secara swasta meskipun Mahmud Yunus telah memperjuangkannya untuk dijadikan sebagai sekolah negeri. Pada tahun 1950, Yunus mengusulkan kepada pemerintah untuk mengompromikan kurikulum yang diterapkan di Sumatera dengan kurikulum nasional. Usul ini dibahas bersama dalam panitia yang dipimpin Mr. Hadi dari Departemen Pendidikan dan Pengajaran dan Mahmud Yunus sendiri dari Departemen Agama. Pada 20 Juanuari 1951, pendidikan agama mulai diajarkan untuk setiap jenjang pendidikan sekolah negeri dan swsata, mulai dari sekolah rendah, lanjutan tingkat pertama dan atas, hingga sekolah kejuruan dengan lama dua jam dalam seminggu. Usaha untuk memajukan pendidikan Islam terus dilakukan Mahmud Yunus bersama tokoh Islam lainnya dimana pada tahun 1945, sidang umum Masjoemi (Majelis Sjoero Moeslimin Indonesia) dilaksanakan yang dihadiri oleh beberapa tokoh politik terkemuka masa itu diantaranya Dr. Mohammad Hatta (Wakil Presiden Pertama Indonesia), Mohammad Natsir, Mr. Mohamad Roem, K.H. Wahid Hasjim. Salah satu keputusan dari pertemuan ini adalah pembentukan Sekolah Tinggi Islam (STI) yang didirikan pada tanggal 8 Juli 1945 bertepatan dengan 27 Rajab 1364 H. Bagi Mahmud Yunus pendirian STI tidak terlepas dari upaya yang pernah dilakukan ketika ia di Padang yang pernah mendirikan STI. Seiring dengan situasi politik di tanah air, pada 1946, STI dipindahkan ke Yogyakarta mengikuti kepindahan ibu kota negara. Dalam perjalanannya STI berganti nama menjadi universitas yang sekarang bernama Universitas Islam Indonesia (UII) yang pada 22 Maret 1948 STI berubah menjadi salah satu fakultas yaitu Fakultas Agma Islam. Melalui Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950 Fakultas Agama UII berubah menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Untuk mengembangkan PTAIN, Mahmud Yunus mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mendirikan PTAIN di Jakarta, meskipun usulan tersebut ditolak dengan alasan sudah PTAIN Yogyakarta. Pada 1 Juni 1957, pemerintah pusat melalui Departemen Agama mendirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta dimana Mahmud Yunus diangkat sebagai Rektor pertama ADIA dan sebagai wakil rektor ditunjuk Bustami Abdul Gani. Dalam perjalanannya karir dan hidupnya, Mahmud Yunus terus berjuang dalam pengembangan pendidikan Islam termasuk pendidikan tinggi Islam dimana ia mengusulkan kepada Menteri Agama agar ADIA di Jakarta terintegrasi dengan PTAIN di Yogyakarta. Usul tersebut mendapatkan persetujuan dari Mentri Agama K.H. Wahib Wahab. Tindak lanjut dari usaha tersebut, Pemerintah mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta yang cikal bakalnya dari Fakultas Agama UII (Yogyakarta) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950. Penetapan PTAIN sebagai perguruan tinggi negeri diresmikan pada tanggal 26 September 1951 dengan jurusan Da'wah (kelak Ushuluddin), Qodlo (kelak menjadi Syari'ah) dan Pendidikan (Tarbiyah). Sementara di Jakarta, berdiri Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) pada 14 Agustus 1957 berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957. Diawali dari penegerian Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia (UII) menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN) di Yogyakarta yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 1950 Tanggal 14 Agustus 1950 dan Peresmian PTAIN pada tanggal 26 September 1951 dan di Jakarta berdiri Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang bernama ADIA berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), maka PTAIN Yogyakarta dan ADIA Jakarta menjadi IAIN "Al-Jami'ah al-Islamiah al-Hukumiyah". IAIN ini diresmikan tanggal 24 Agustus 1960 di Yogyakarta oleh Menteri Agama K. H. Wahib Wahab. Sejak tanggal 1 Juli 1965 nama "IAIN Al-Jami'ah" di Yogyakarta diganti menjadi "IAIN Sunan Kalijaga". Dalam perjalannya berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 49 Tahun 1963 tertanggal 25 Februari 1963 dibentuk IAIN kedua di Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. IAIN Yogyakarta dalam perjalanannya menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sedangkan IAIN Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. (MusAm)